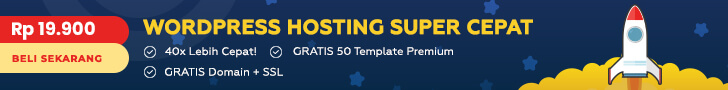Oleh: Zaenuddin Endy (Koordinator LTN Thariqiyah Imdadiyah JATMAN Sulawesi Selatan)
Syekh Abdul Majid bin Syekh Abdul Hayyi merupakan salah satu ulama Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah intelektual Islam di Sulawesi Selatan, terutama melalui karya penyalinan mushaf Al-Qur’an yang ia hasilkan pada pertengahan abad ke-19. Namun, di balik peran intelektualnya sebagai penyalin mushaf, terdapat jejak spiritual yang menarik untuk dilacak, yakni keterhubungannya dengan tradisi tarekat, khususnya kemungkinan afiliasinya dengan jaringan Tarekat Sanusiyah Idrisiyah. Tarekat ini dikenal sebagai salah satu tarekat pembaharu yang berkembang di dunia Islam abad ke-19, berasal dari Libya, dan menyebar ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara melalui jaringan ulama Haramain.
Tarekat Sanusiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi (1787–1859) menekankan pentingnya kesederhanaan hidup, penguatan tauhid, dan militansi dakwah. Jaringan tarekat ini banyak diikuti oleh ulama yang pernah menuntut ilmu di Makkah, karena di kota suci tersebut as-Sanusi sempat bermukim sebelum kembali ke Afrika Utara. Sanusiyah juga dikenal sebagai tarekat yang terlibat dalam perjuangan politik melawan kolonialisme Barat, sehingga daya tariknya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-politik. Hal ini sesuai dengan situasi di Nusantara abad ke-19, di mana Islam sering menjadi basis moral perlawanan rakyat terhadap penetrasi Belanda.
Dalam konteks Bugis, khususnya Bone, ulama-ulama lokal pada abad ke-19 memiliki hubungan erat dengan Haramain. Banyak di antara mereka yang bermukim atau belajar di Makkah dalam waktu lama, lalu kembali dengan membawa sanad ilmu, tarekat, bahkan jaringan dagang. Keluarga Syekh Abdul Hayyi dari Pompanua, Bone, termasuk dalam kategori ini. Syekh Abdul Majid, sebagai putra dari ulama besar tersebut, mewarisi tradisi keilmuan sekaligus spiritualitas yang didapat melalui jalur internasional. Di sinilah kemungkinan keterhubungan dengan Tarekat Sanusiyah Idrisiyah perlu ditinjau, mengingat eksistensi tarekat ini di Haramain cukup menonjol pada masanya.
Sanusiyah memiliki kedekatan dengan tradisi Idrisiyah, sebuah tarekat yang lebih tua yang berakar pada warisan Sayyid Ahmad bin Idris al-Fasi (1760–1837). Dari Ahmad bin Idris inilah kemudian lahir berbagai cabang tarekat pembaharu, termasuk Sanusiyah. Idrisiyah menekankan pada kesederhanaan, kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah, serta memperkuat ikatan sanad antara mursyid dan murid. Karakter inilah yang sangat mungkin menarik bagi para ulama Bugis, termasuk Syekh Abdul Majid, yang dalam kesehariannya sudah dikenal tekun dalam mushaf, disiplin dalam zikir, dan kuat dalam menjaga tradisi ilmu.
Perlu dicatat bahwa tarekat di Nusantara tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali bercampur dalam bentuk sinkretik dengan tarekat lain seperti Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dengan demikian, meskipun Sanusiyah tidak secara eksplisit disebut-sebut dalam manuskrip lokal Bugis, jejak pemikiran dan praksisnya bisa saja masuk melalui ulama Bugis yang berinteraksi dengan jaringan global Islam di Haramain. Syekh Abdul Majid yang lahir dan besar dalam keluarga ulama penyalin mushaf sangat mungkin terhubung dengan tradisi ini, karena aktivitas menulis mushaf erat kaitannya dengan riyadhah rohani, wirid, dan suluk yang sejalan dengan amalan tarekat.
Dalam dunia tarekat, khususnya Sanusiyah-Idrisiyah, mushaf Al-Qur’an dipandang bukan hanya teks, tetapi cahaya ilahi yang harus dihidupkan dengan zikir dan amal. Menyalin mushaf dengan tangan merupakan bentuk dzikir bil-qalam, sebuah ibadah yang menuntut kesabaran, kejernihan batin, dan pengendalian diri. Aktivitas Syekh Abdul Majid ini menguatkan indikasi bahwa dirinya tidak hanya ulama intelektual, tetapi juga seorang sufi yang mengamalkan laku tarekat.
Di sisi lain, karakter perlawanan Sanusiyah terhadap kolonialisme menemukan resonansinya di tanah Bugis. Pada abad ke-19, wilayah Bone dan sekitarnya mengalami tekanan politik dari Belanda. Ulama tarekat sering kali tampil sebagai penggerak moral perlawanan, baik dalam bentuk jihad fisik maupun dalam bentuk jihad kultural dan spiritual. Syekh Abdul Majid, melalui aktivitas intelektual dan spiritualnya, memberikan kontribusi dalam menjaga semangat masyarakat Bugis agar tetap berpegang teguh pada Islam di tengah tekanan kolonial.
Tradisi tarekat Sanusiyah Idrisiyah juga dikenal dengan sistem organisasi yang rapi, berupa ribath atau zawiyah sebagai pusat pengajaran dan pembinaan murid. Meskipun tidak ditemukan bukti eksplisit adanya zawiyah Sanusiyah di Bone, pola halaqah dan pengajian keluarga ulama Pompanua mencerminkan fungsi serupa. Murid-murid belajar bukan hanya ilmu Al-Qur’an, tetapi juga adab, wirid, dan laku spiritual. Dengan demikian, tradisi ini sejalan dengan pola pendidikan tarekat yang lebih luas.
Jejak intelektual Syekh Abdul Majid juga memperlihatkan keterhubungan antara dunia manuskrip dan dunia tarekat. Mushaf yang ia tulis menjadi artefak historis sekaligus simbol spiritual. Manuskrip itu tidak hanya menunjukkan keterampilan seni kaligrafi, tetapi juga kekuatan rohani yang mengiringi setiap huruf yang ditulis. Ini sesuai dengan pandangan Idrisiyah bahwa setiap huruf Al-Qur’an mengandung cahaya yang dapat menuntun hati menuju Allah.
Dalam lintasan sejarah, pengaruh Idrisiyah di Nusantara memang lebih kuat di Sumatra Barat melalui ulama-ulama Minangkabau yang belajar kepada Ahmad bin Idris atau murid-muridnya. Namun, bukan berarti pengaruh itu tidak sampai ke Bugis. Sebab, jaringan haji dan ulama Sulawesi Selatan abad ke-19 banyak terhubung dengan jaringan yang sama di Haramain. Karena itu, Syekh Abdul Majid mungkin termasuk ulama yang menyerap semangat tarekat ini, meski tidak secara formal tercatat sebagai mursyid Sanusiyah.
Warisan yang paling jelas dari peran Syekh Abdul Majid adalah kesinambungan tradisi penyalinan mushaf di Pompanua. Namun, jika dilihat lebih dalam, tradisi itu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan habitus spiritual tarekat. Sanusiyah-Idrisiyah yang menekankan tauhid murni, kesederhanaan hidup, serta kedekatan murid dengan mursyid, memiliki kesamaan dengan corak keberagamaan masyarakat Bugis yang menghargai adat, kejujuran, dan kepatuhan kepada guru.
Dalam kerangka sejarah sosial, kehadiran ulama seperti Syekh Abdul Majid memperlihatkan bahwa Islam Bugis bukan hanya hasil proses politik dan dakwah formal, tetapi juga buah dari jaringan spiritual tarekat internasional. Tarekat menjadi ruang yang mempertautkan dimensi global Islam dengan praktik lokal, dan dalam konteks ini, Sanusiyah-Idrisiyah memberi kontribusi dalam pembentukan spiritualitas masyarakat Bugis.
Syekh Abdul Majid dengan demikian bukan hanya penyalin mushaf, tetapi juga penjaga tradisi tarekat yang halus, yang menyalurkan pengaruh Idrisiyah-Sanusiyah melalui amal sehari-hari, pengajaran, dan karya tulisnya. Ia adalah representasi ulama yang menjembatani teks dan praksis, manuskrip dan zikir, ilmu dan amal.
Seiring waktu, jejak Sanusiyah di Bugis mungkin tidak berkembang menjadi organisasi besar seperti di Afrika Utara, tetapi pengaruh spiritualnya tetap hidup dalam tradisi keilmuan, pengajian, dan adat Islam lokal. Syekh Abdul Majid bin Syekh Abdul Hayyi menjadi salah satu simpul penting dalam sejarah ini, yang layak dikaji lebih jauh sebagai bagian dari jaringan global tarekat pada abad ke-19.
Dengan demikian, sejarah Syekh Abdul Majid memperlihatkan bagaimana ulama lokal Bugis mampu menyerap arus besar pembaruan tarekat internasional, lalu mengintegrasikannya ke dalam tradisi lokal. Sanusiyah-Idrisiyah memberi warna pada spiritualitasnya, sementara aktivitas penyalinan mushaf menjadi bukti nyata integrasi ilmu dan amal yang diwariskan bagi generasi setelahnya.